-
Sia-Sia Mengharapkan Cintamu
-

New Masyarakat.net
-
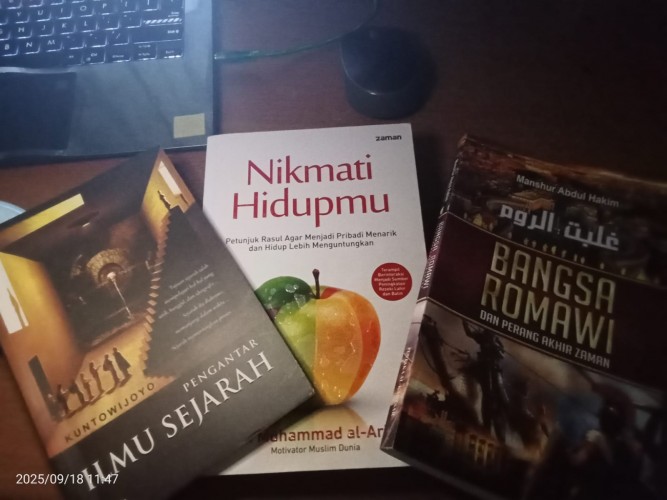
Sia-Sia Mengharapkan Cintamu (Aras)
(Edukasi Santai Dan Mudah Dalam Memahami Kondisi Demokrasi Di Indonesia Saat Ini)
Dr. H. J. Faisal
Seperti lagunya Gustrian Geno yang sedang saya dengarkan sekarang, yang berjudul ‘Sia-sia Mengharapkan Cintamu’....begitulah representasi kekecewaan saya sebagai rakyat negara ini terhadap mereka para wakil rakyat yang duduk di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun kekecewaan terhadap para petinggi negara ini dengan mega korupsi mereka, dengan gaya hidup mewah mereka, dengan kekerdilan mental negarawan mereka, dengan kesimpulan akhir, sepertinya mereka lebih pantas menjadi perampok daripada menjadi pemimpin.
Ketika para petinggi negara dan para wakil rakyat lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga amanah, ketika petinggi negara lebih bangga dengan mobil dinas daripada moral dinas, maka saya, bahkan mungkin anda sebagai rakyat pun mulai bertanya…..“Apakah mereka ini pemimpin, atau hanya perampok yang berseragam dengan pin pejabat di baju safari mereka, ya?”
Korupsi bukan lagi insiden, tetapi rutinitas. Gaya hidup mewah bukan lagi pencapaian, tetapi pameran. Mental negarawan yang seharusnya besar, malah kerdil di hadapan godaan kekuasaan.
Maka, lagu dari Gustrian Geno yang sedang saya dengarkan sekarang sebenarnya bukan untuk cinta yang hilang, tetapi lebih tepat untuk harapan yang dikhianati.
Demokrasi Rasa Instan, Dari Musyawarah ke Voting, dari Pancasila ke Amerika Serikat
Ingatan saya juga langsung melayang kembali ke era awal reformasi tahun 1998 dahulu. Kebetulan saya sedang duduk di semester 4 pada tahun itu, dan pastinya ‘ikut berpartisipasi’ menurunkan sang Jenderal Soeharto sebagai Presiden ke-2 negara ini.
Namun yang menjadi pertanyaan besar saya saat ini adalah, apakah peristiwa reformasi 1998 pada waktu itu saya dan anda lakoni Bersama merupakan titik balik atau titik belok bangsa ini, ya?
Mengapa saya bertanya demikian?
Karena menurut saya, dalam euforia reformasi 1998 itu, bangsa Indonesia seolah menemukan cawan suci bernama “demokrasi langsung,” yang jelas-jelas merupakan isi dari sistem demokrasi liberal.
Dan seperti anak muda yang baru kenal kopi, kita sebagai anak bangsa yang masih awam tentang apa itu demokrasi yang sebenarnya, langsung pesan espresso double shot, tanpa tahu bahwa lambung kita ternyata belum siap. Demokrasi liberal pun diseruput dengan semangat, meski pahitnya baru terasa belakangan ini.
Padahal sejatinya, sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah punya resep demokrasi sendiri, yaitu musyawarah untuk mufakat.
Bukan voting, bukan suara terbanyak, tetapi kebijaksanaan kolektif. Tetapi entah kenapa, resep warisan para pejuang dan pendiri negara ini justru dianggap kuno, tidak Instagrammable, dan diganti dengan menu ala Barat yang katanya lebih modern.
Ironisnya, negara yang jadi panutan demokrasi itu sendiri, yaitu Amerika Serikat, justru tidak sepenuhnya percaya pada suara rakyat. Mereka punya Electoral College, sistem perwakilan yang lebih mirip musyawarah elit daripada pesta rakyat.
Lah kita, yang katanya baru belajar demokrasi, malah sok-sokan pakai sistem pemilihan langsung.
Akhirnya, reformasi pun menjadi ajang makeover konstitusi. UUD 1945 yang dulu sakral, kini sudah dirombak berkali-kali seperti brosur promosi.
Amandemen demi amandemen UUD dilakukan selama empat kali sampai tahun 2002, katanya demi memperkuat demokrasi. Tetapi yang terjadi justru pelemahan semangat kolektif dan penguatan individualisme politik.
Misalnya, sistem pemilihan presiden langsung dianggap sebagai puncak demokrasi. Rakyat diberi hak memilih, tetapi tidak diberi bekal memahami.
Akibatnya, pemilu berubah jadi kontes popularitas, bukan seleksi kenegarawanan. Yang penting viral, bukan visioner. Yang penting banyak uang, kualitas diri nomer tiga puluh dua.
Padahal, negara Amerika Serikat, yang sering disebut sebagai “mbahnya demokrasi”, dan sebagai negara ‘eksportir demokrasi’ yang menjadi kiblat demokrasi bangsa Indonesia selama 50 tahun terakhir ini, justru menggunakan sistem yang tidak sepenuhnya demokrasi langsung dalam memilih presidennya. Sistem itu disebut Electoral College.
Dalam sistem Electoral College ini, warga Amerika tidak memilih presidennya secara langsung, melainkan memilih elektor dari partai yang mereka dukung, dan elektor ini adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan suara resmi untuk menentukan siapa yang jadi presiden.
Adapun jumlah elektor keseluruhannya adalah 538 orang, dimana setiap negara bagiannya mempunyai jumlah elektor yang berbeda, tergantung populasi dan jumlah anggota kongresnya (congressman) di parlemen.
Misalnya, California punya 55 elektor, sedangkan negara bagian kecil seperti Wyoming hanya punya 3 elektor.
Jadi, jika misalnya kandidat presiden A menang suara terbanyak di satu negara bagian, maka dia dapat semua suara elektoral dari negara bagian itu.
Dan dari total 538 suara elektoral, kandidat harus meraih minimal 270 suara untuk menang.
Sehingga, meskipun kalah dalam popular vote secara nasional, seseorang bisa tetap jadi presiden kalau menang di negara bagian yang punya banyak elektor. Dan ini pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah Amerika.
Pertanyaannya adalah, kenapa Amerika malah menggunakan sistem tidak langsung seperti ini?
Jawabannya Adalah karena mereka ingin ada “filter” berupa elector, yang dianggap lebih bijak dan terdidik dalam memilih pemimpin. Sistem ini awalnya dirancang oleh para pendiri negara untuk menghindari dominasi populasi besar dan memberi suara pada negara bagian kecil.
Tetapi ya, sistem ini juga menuai banyak kritik karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.
Namun demi menghormati para pendiri negara mereka, sampai sekarang pun mereka masih gunakan sistem ini,
Ironis, bukan? Negara yang jadi simbol demokrasi malah menggunakan sistem yang lebih mirip perwakilan elit dan pemusyarakatan.
Laaah…..kita negara yang belum paham tentang demokrasi liberal, malah bertingkah seperti negara yang paling mengerti tentang demokrasi jenis ini.
Padahal para pendiri negara kita sudah memberikan formula demokrasi yang sangat adaptif dengan kutur dan budaya bangsa ini, yaitu demokrasi permusyawaratan dan keterwakilan dalam kekhidmatan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang asli.
Jika kita pelajari lebih mendalam, sejatinya demokrasi yang dibawa Amerika, dan selalu digembar-gemborkan itu belum tentu cocok untuk diterapkan di semua negara, termasuk indonesia.
Ingat, Indonesia itu menganut sistem kesatuan, bukan federasi, artinya semua keputusan tingkat tinggi bahkan sampai pemilihan presiden pun seharusnya dilakukan berdasarkan pemusyarakatan di MPR.
UUD 1945 memang mengakui sistem demokrasi, termasuk pemilihan umum sebagai sarana memilih wakil rakyat dan pemimpin negara.
Namun, pemilihan langsung bukan satu-satunya bentuk pengambilan keputusan yang disarankan. Dalam konteks legislatif dan pemerintahan, musyawarah dan mufakat tetap menjadi metode utama, terutama dalam proses legislasi dan kebijakan publik3.
Bahkan dalam sistem perwakilan, wakil rakyat diharapkan menjalankan tugasnya dengan semangat permusyawaratan, bukan sekadar mengikuti suara mayoritas.
Jadi, jika kita ingin menjadi benar secara filosofis dan normatif, maka Indonesia harus menganut demokrasi yang berakar pada musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan UUD kita dan Pancasila, bukan demokrasi liberal yang sepenuhnya bergantung pada voting. Pemilihan langsung adalah instrumen demokrasi, tetapi bukan satu-satunya cara yang direkomendasikan oleh konstitusi dan Pancasila.
Demokrasi Liberal Adalah Senjata Yang Sangat Mematikan Untuk Negara Bermental Feodal, Seperti Indonesia
Sejatinya, demokrasi yang bersifat liberal bahkan neo liberal, adalah senjata yang sangat mematikan yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menguasai 'legitimasi' sebuah negara berkembang yang sangat lemah kekuatan diplomasinya, dan tidak mmampu melindungi dirinya sendiri dari serbuan ideologi politik, ya seperti negara Indonesia ini.
Sudah banyak akademisi serta pengamat geopolitik yang juga mengangkat isu serupa. Demokrasi, dalam konteks global, memang bukan sekadar sistem pemerintahan. Dia bisa menjadi alat diplomasi, instrumen pengaruh, bahkan senjata ideologis yang digunakan oleh negara-negara besar untuk membentuk lanskap politik negara lain sesuai kepentingan mereka.
Amerika Serikat sering memposisikan diri sebagai eksportir demokrasi. Tetapi ekspor ini isinya bukan cuma soal nilai luhur, melainkan juga soal strategi geopolitik mereka untuk menguasai negara incaran mereka, dengan iming-iming bahwa negara yang mengadopsi sistem demokrasi liberal cenderung lebih mudah diterima dalam forum internasional, mendapat bantuan, dan dianggap “beradab.”
Indonesia, sebagai negara dengan sejarah panjang musyawarah dan kolektivitas, semakin terlihat tergopoh-gopoh dan ngos-ngosan dalam menjalankan demokrasi model begini, karena dipaksa menyesuaikan diri dengan format demokrasi liberal, misalnya dengan praktek pemilu langsung yang mahal dan rawan manipulasi, partai politik yang lebih sibuk memburu suara daripada membangun ideologi, dan media massa yang lebih menyorot drama politik daripada substansi kebijakan.
-
Baca Juga :
-
Padahal, ketika negara berkembang gagal menjalankan demokrasi versi Barat (baca: liberal dan sekular), maka terbuka ruang bagi intervensi, baik lewat tekanan diplomatik, sanksi, atau bahkan dukungan terhadap oposisi.
Mengapa demikian? Ya, karena demokrasi liberal membawa serta nilai-nilai individualisme, pasar bebas, dan kebebasan absolut yang kadang bertabrakan dengan budaya kolektif negara penganutnya.
Akibatnya, demokrasi kita kadang lebih mirip dekorasi politik daripada sistem yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Kita punya semua atribut demokrasi, yaitu pemilu, partai, parlemen, tetapi substansi musyawarah dan kebijaksanaan sering hilang di tengah hiruk-pikuk suara mayoritas.
Dengan kemampuan diplomasi lemah, dan ideologi yang terbuka dan tidak pasti, maka negara ‘mengambang’ seperti Indonesia sering kali tidak punya daya tawar diplomatik yang kuat. Ketika tekanan internasional datang, kita cenderung mengikuti arus, bukan membentuk arus. Demokrasi pun jadi pintu masuk bagi ideologi asing, bukan wadah ekspresi nilai lokal.
Itulah kenapa demokrasi liberal bisa jadi senjata yang mematikan, bukan karena sistemnya buruk, tetapi karena cara penggunaannya yang manipulatif. Kalau kita tidak punya mentalitas kuat, diplomasi cerdas, dan budaya politik yang kokoh, maka kita akan terus jadi panggung bagi kepentingan asing, bukan aktor utama dalam cerita kita sendiri.
Begitupun dengan aktor-aktor pemimpin negara ‘terbelakang’ tersebut.
Ungkapan bahwa demokrasi adalah senjata yang mematikan bukan berasal dari satu tokoh tunggal secara eksplisit, tetapi gagasan ini sering muncul dalam kajian geopolitik kritis dan teori demokrasi kontemporer. Salah satu yang paling mendekati adalah pemikiran dari Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, penulis buku How Democracies Die.
Mereka menyatakan bahwa:
“Demokrasi tidak mati di tangan seorang jenderal, tapi di tangan para pemimpin terpilih, yaitu presiden atau perdana menteri yang memenangi kontes kekuasaan.”
Artinya, demokrasi juga dapat menjadi alat yang sangat efektif, bahkan mematikan, jika digunakan oleh aktor politik yang manipulatif. Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi bisa menjadi instrumen legitimasi untuk kekuasaan yang otoriter, korup, atau bahkan destruktif.
Masalah Utamanya Adalah Mentalitas
Memang jika mau jujur, sebab masalah utamanya bukan pada sistem, tetapi pada mental bangsa. Demokrasi yang sejati, sangat membutuhkan karakter, bukan sekadar prosedur. Tetapi kita lebih sibuk membahas teknis pemilu daripada membangun etika publik, kata Rocky Gerung.
Demokrasi pun jadi ritual, bukan nilai.
Elit politik kita pun tidak kalah repot. Mereka bicara demokrasi sambil merancang strategi transaksional. Musyawarah diganti dengan lobi, mufakat diganti dengan deal. Demokrasi pun berubah jadi pasar malam, penuh sorak sorai tetapi minim makna.
Nah yang lebih repotnya, rakyat pun ikut-ikutan larut, semudah larutnya gula dan garam (oralit) untuk obat sakit perut.
Mereka memilih bukan karena visi dan edukasi, apalagi karakter pilihannya, tetapi karena amplop dan baliho.
Ya, demokrasi pun menjadi ajang konsumsi politik, bukan partisipasi. Kita memilih seperti belanja di minimarket, cepat, murah, tetapi ternyata barangnya sudah kadaluwarsa, rusak, dan akhirnya menyesal, dah.
Media massa, yang seharusnya jadi pilar keempat demokrasi, justru ikut memperkeruh suasana. Mereka lebih suka menyorot drama politik daripada mendidik publik. Demokrasi pun jadi infotainment, bukan pendidikan politik.
Pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi? Boro-boro, jangan harap. Politik katanya ‘haram’ untuk dibahas di sekolah, bahkan di pendidikan tinggi. Takut ‘disemprit’ pimpinan atau Rektor, dan jadi ‘incaran’ rezim, katanya. Hehehehe…..
Pancasila hanya jadi hafalan, bukan pengamalan. Musyawarah hanya jadi simulasi, bukan budaya. Anak-anak diajarkan voting, tetapi tidak diajarkan mendengar.
Akhirnya, ya gitu deh….demokrasi pun tumbuh cacat sejak dini. Seperti yang kita alami turun temurun selama ini.
Refleksi Demokrasi di Indonesia
Dalam kondisi seperti ini, wacana amandemen UUD untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR memang terdengar seperti nostalgia. Tetapi mungkin nostalgia itu perlu, agar kita ingat bahwa demokrasi bukan sekadar suara terbanyak, tetapi suara yang bijak.
Wacana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR kini malah dianggap retro, tidak progresif, bahkan anti-demokrasi.
Padahal, jika kita jujur, sistem itu justru lebih sesuai dengan semangat Pancasila. Tetapi siapa yang peduli? Yang penting kita terlihat demokratis di mata dunia.
Demokrasi kita pun menjadi demokrasi kosmetik.
Ada pemilu, ada partai, ada kampanye, tetapi substansinya kosong. Seperti gedung megah tanpa fondasi, tinggal tunggu waktu roboh. Dan ketika roboh, kita akan menyalahkan sistem, bukan mentalitas.
Ya tentu saja, sistem pemilihan oleh MPR juga punya kelemahan. Bisa jadi ajang elitisme, bisa jadi ruang transaksi. Tetapi setidaknya, sistem itu punya semangat kolektif.
Tidak seperti pemilihan langsung yang sering kali hanya menghasilkan pemimpin yang pandai bicara, bukan pandai berpikir, yang hanya banyak duit, tanpa kualitas diri. Bahkan mantan koruptor dan mantan pembunuh pun bisa menjadi wakil rakyat.
Edan, bukan?
Demokrasi Pancasila bukan anti-rakyat, tetapi pro-kebijaksanaan. Dia tidak menolak partisipasi, tetapi mengarahkan partisipasi pada dialog, bukan duel.
Tetapi sayangnya, kita lebih suka berdebat daripada berdiskusi. Demokrasi pun jadi arena, bukan ruang bersama.
Dalam situasi ini, mungkin kita perlu jeda. Bukan untuk mundur, tetapi untuk refleksi.
Apakah demokrasi kita masih punya jiwa, atau hanya tinggal jasad? Apakah kita masih percaya pada musyawarah, atau sudah menyerah pada suara terbanyak?
Etika dan Moral Dalam Demokrasi
Tentu saja, demokrasi bukanlah tujuan, tetapi jalan. Dan jalan itu harus dibangun dengan karakter, bukan hanya regulasi. Kalau mentalitas bangsa belum siap, maka sistem apapun akan gagal. Demokrasi pun akan jadi ilusi, bukan solusi.
Maka, sebelum bicara sistem, mari kita bicara manusianya dulu. Sebelum bicara pemilu, mari bicara etika. Sebelum bicara reformasi, mari bicara refleksi. Sebab demokrasi sejati lahir dari jiwa yang merdeka, bukan dari prosedur yang dipaksakan.
Dan jika suatu hari kita benar-benar ingin kembali ke demokrasi Pancasila, jangan mulai dari amandemen, tetapi mulailah dari kesadaran hati dan pemahaman akademis.
Dari diskusi dan penilaian ruang kelas akademis, dari ruang keluarga, dari ruang publik. Sebab musyawarah bukan sekadar metode, tetapi budaya luhur negeri ini.
Dan budaya itu harus ditanam, bukan diimpor.
Jadi di Indonesia ini, demokrasinya hanya sebagai dekorasi atau hanya akan melahirkan monster yang bernama democrazy?
Okelah kalau begitu….
Jika sudah paham dan saling memahami, saya lanjutkan dengarkan lagunya Gustrian Geno yaaa…..‘Sia-sia Mengharapkan Cintamu....’ Wallahu’allam bisshowab
Jakarta, 18 September 2025
*Pensyarah UNIDA Bogor/ Director of Logos Institute for Education and Sociology Studies (LIESS) / Pemerhati Pendidikan dan Sosial/ Anggota PJMI
-
Update Info Covid 19 Nasional dan Internasional Disini:
-
Tag :
-
Komentar :
-
Share :
















